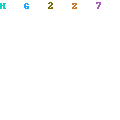Wajah administasi suatu negara merupakan produk dari sistem politik, posisi perkembangan ekonomi dan sosial dari negara yang bersangkutan, di samping sebaliknya dalam banyak hal administrasi negara juga menentukan penampilan sistem politik, perkembangan ekonomi dan kualitas sosial negara itu. Oleh karena itu seharusnya diskusi tentang sejarah administrasi negara Republik Indonesia ini dilakukan di tengah-tengah dan bersamaan dengan pembahasan tentang sejarah pemerintahan dan politik. Tetapi penulis berpendapat bahwa jika cara itu ditempuh, maka pembaca akan dituntut untuk menyerap terlalu banyak tema informasi sekaligus sehingga menyulitkan penyerapan dan pemahamannya. Atas dasar itu "sejarah" administrasi RI disajikan dalam bab tersendiri di sini. Namun harus dicatat, bahwa karena konsep-konsep perubahan, penyempurnaan, modernisasi atau reformasi administrasi dipraktikkan oleh hampir semua pemerintahan, maka uraian tentang konsep-konsep ini tidak dapat dipandang sebagai perkembangan praktik yang linear dari administrasi negara RI melainkan lebih banyak menunjuk pada perkembangan popularitas konsep itu di kalangan para pejabat dan ilmuwan administrasi. Menurut bacaan penulis, istilah yang digunakan oleh pejabat dan ilmuwan kita secara berturut-turut adalah: rasionalisasi administrasi, administrasi pembangunan, penyempurnaan administrasi, reformasi administrasi, dan pembaharuan atau modernisasi administrasi. Model, konsep atau istilah ini sudah mulai dikenal pada fase pendahulunya dan biasanya masih pula dipakai pada fase sesudahnya. Dengan kata lain, penggunaan atau penerapan suatu model tidak berarti hilangnya model yang lain, atau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dimaksudkan "model" di bawah ini sebenarnya hanyalah "mode" penggunaan istilah --dengan nama yang berbeda memiliki esensi yang sama.
1. Rasionalisasi administrasi: mengatasi kelangkaan dana
Sejarah pemerintahan RI pada bagian depan telah memperlihatkan bahwa Republik Indonesia adalah negara-kelanjutan dari Hindia Belanda. Artinya struktur negara RI bukanlah struktur yang baru, dan dalam sangat banyak hal malah melanjutkan --jika bukannya melestarikan-- budaya dan perilakunya. Euphoria kemerdekaan 1945 untuk sementara menghasilkan pemerintahan pada 1950-an yang bersifat relatif demokratis, ada puluhan partai politik dan pemerintahannya bersistem parlementer. Namun, berlawanan dengan nilai demokrasi, dalam negara "baru" ini para politisi mengatur sistem administrasi hingga pada penempatan personalianya, dimana jabatan administrasi tampaknya dipandang sebagai imbalan bagi kemenangan politik mereka. Sistem politik yang demokratis menghasilkan perubahan pemerintahan yang sangat sering, dan dalam tubuh administrasi terjadi penyalahgunaan wewenang. Ini disadari oleh politisi manapun. Karena itu, melawan praktik mereka sendiri, berbagai pemerintahan dari partai manapun berusaha melakukan perbaikan sistem adminstrasi dari tahun ke tahun yang salah satu nilainya adalah: rasional, the right man on the right place.
Penyimpangan praktik administrasi atau maladministrasi yang ditandai dengan menurunnya atau tiadanya disiplin, ketekunan, ketelitian, kecermatan dan semangat kerja --yang dengan mudah tertumpangi oleh korupsi-- disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, situasi transisi menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan kerja, sehingga kebanyakan pegawai "menyelamatkan diri sendiri"; ke-dua, pejabat yang duduk di dalam birokrasi kebanyakan adalah pejabat lama yang sebelumnya merupakan pegawai Hindia Belanda, yang berorientasi bukan kepada prestasi melainkan askripsi (lihat bab sebelumnya); dan ke-tiga, masih sangat sedikitnya jumlah profesional modern yang dapat ditarik ke dalam birokrasi. Memang praktik administrasi kolonial Belanda sejak Daendels (sekitar 1810) telah dapat disebut sebagai administrasi negara "modern", tetapi tidak banyak orang Indonesia yang bekerja di dalamnya apalagi memegang jabatan pimpinan dan lebih dari itu mereka cenderung mempertahankan gaya patrimonial yang askriptif. Sementara itu organisasi pergerakan nasional yang pertama pada awal abad ke-20 seperti Boedi Oetomo dan Muhammadiyah serta organisasi pergerakan berikutnya seperti Syarekat Dagang Islam dan Partai Komunis Indonesia tentunya juga sudah mengenal adminstrasi modern itu, tetapi ketika negara Indonesia terbentuk tidak dijumpai tenaga terdidik dalam jumlah yang memadai di bidang ini.
Hal itu disadari sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga setelah RI dalam kondisi relatif normal, sukses memenangkan pengakuan internasional, pemerintah mulai berusaha memecahkan penyebab yang ke-tiga, yakni kelangkaan tenaga profesional di bidang administrasi negara. Sejak 1951 hingga 1955 diperkenalkanlah ilmu administrasi negara "modern", jauh lebih belakangan dibanding pengenalan ilmu hukum dan ekonomi --serta teknik dan kedokteran-- yang telah dimulai sejak 1900-an. Ilmu administrasi yang diintrodusir pada paruh pertama dasawarsa 1950-an ini berorientasi ke Amerika Serikat, yang dipandang lebih praktis dan pragmatis dibanding sistem administrasi kolonial Belanda yang bersifat legalistik. Pengintroduksiannya dilakukan melalui pembentukan jurusan administrasi negara di Universitas Indonesia (UI) di Jakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.
Pengenalan di bidang akademik itu berlangsung berbarengan dengan usaha rasionalisasi organisasi pemerintah Pusat oleh Kabinet Wilopo yang berumur sekitar 15 bulan (3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953). Kabinet berikutnya yang dipimpin Ali Sastroamidjojo (berumur dua tahun, 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955) mempunyai program yang antara lain berisi: (a) menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai dan (b) memberantas korupsi dan birokrasi. Terlihat dari visi kedua kabinet di awal RI yang baru ini, bahwa sistem administrasi hendaklah disusun secara rasional: sederhana, mudah dan tidak birokratis, dimana para pegawainya yang sejahtera dapat bekerja secara efisien dan tidak memungkinkan terjadinya korupsi. Visi seperti ini terus dibawa pada masa-masa berikutnya, ditambah dengan peningkatan kemampuan pegawai. Program berikutnya adalah pembentukan Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian (PANOK, 1952-1954). Pada 1953 T.R. Smith dari USA menyusun laporan untuk Biro Perancang Negara berjudul Public Administration Training. Setahun kemudian dua orang profesor dari Amerika yang diundang ke Indonesia, Edward H. Lichtfeld dan Alan C. Rankin, menyusun laporan rekomendasi yang berjudul Training for Administration in Indonesia.
Selanjutnya pada 1957 dibentuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yang hingga kini punya peran yang menentukan terhadap penampilan birokrasi Indonesia, pada 1962 dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dan pada 1964 Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR). Retooling atau "pembersihan" dalam dua kepanitian terakhir bernuansa politis: menyingkirkan pegawai yang tak sehaluan dengan partai yang sedang memerintah (the ruling party). Dengan kata lain birokrasi di Indonesia pada dua dasawarsa pertama ini bersifat spoil system --situasi yang juga sangat dominan selama tahun-tahun pertama pemerintahan Amerika Serikat abad-18. Sementara itu pada 1958, sebagai imbas dari politik luar negeri Indonesia yang berusaha untuk membangun solidaritas regional Asia Tenggara, Indonesia mengikuti sebuah konferensi di Manila yang kemudian membentuk organisasi Eastern Regional Organisation for Public Administration (EROPA). Kecuali itu Indonesia juga menjalin hubungan dengan International Institute for Administrative Science (IIAS) di Brussel. Sesudah itu hingga 1965 dijumpai banyak tulisan tentang administrasi pada umumnya dan administrasi negara pada khususnya oleh penulis-penulis seperti Prajudi Atmosudirdjo, Awaloedin Djamin, Achmad Sanusi, Tobias Subekti, Soejoed, Sondang P. Siagian, Sujoto, The Liang Gie, Daoed Joesoef, J.E. Ismail dan Kosim Adisaputra. Penulis yang terakhir ini meletakkan embrio pemikiran tentang administrai pembangunan di Indonesia yang akan dijelaskan di belakang.
Instabilitas politik dan ketidaknetralan birokrasi merupakan dua isu penting yang hendak dikoreksi oleh Presiden RI ke-dua, Soeharto, yang memerintah sejak Juli 1966 dan resmi mulai Maret 1968. Sekalipun sesungguhnya Indonesia era Soekarno telah mencoba mempraktikkan dua sistem ekonomi politik yang saling bertolak-belakang: liberal pada awalnya dan etatis pada akhirnya, pemerintahan Soeharto dalam diskurs publiknya selalu menonjolkan buruknya liberalisme era Soekarno --tentu saja untuk melegitimasi etatisme dalam modelnya. Pada tahun 1967 dibentuklah secara berturut-turut tiga buah tim: tim penyusun daftar susunan pegawai dan peralatan, tim pembantu Ketua Presidium Kabinet Ampera dan tim penertiban aparatur/administrasi pemerintah (Tim PAAP). Masih dengan nafas politis, tim yang terakhir ini diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja, bukannya misalnya Mendagri atau Sekneg. Mereka bertugas untuk merestrukturisasi susunan departemen, mengubah penggolongan pegawai, rasionalisasi serta restrukturisasi perusahaan negara --dengan mengurangi peran negara (deetatisasi), menyederhanakan prosedur administrasi (debirokrasi) antara lain dengan menggolongkan perusahaan negara ke dalam tiga bentuk sesuai dengan besarnya kapital pemerintah di dalamnya (perusahaan jawatan, perusahaan perseroan dan perusahaan umum) dan mengurangi kontrol negara terhadap perusahaan negara (dekontrolisasi). Selanjutnya, tidak ketinggalan, dibentuk pula Tim Pemberantasan Korupsi.
Terlihat pada visi administrasi baik pemerintahan Soekarno(-Hatta) maupun Soeharto di atas bahwa pemerintah Indonesia sejak awal telah meyakini ide-ide administrasi yang rasional, tidak nepotis, tidak berbelit-belit dan tidak korup. Namun berbeda dengan visi, fase bernegara yang masih sangat muda pada era Soekarno terbukti tidak mampu menahan nepotisme yang berakibat pada korupsi. Bahkan usaha rasionalisasi militer yang dirancang oleh AH Nasution (dan Hatta) menghasilkan resistensi yang meletus sebagai pemberontakan di beberapa daerah (lihat bab depan). Bagaimana dengan era Soeharto? Berturut-turut selama 32 tahun pemerintahannya penyempurnaan administrasi sesungguhnya menjadi salah satu program yang dipertahankannya. Tetapi stabilitas politik yang cenderung monolitik memungkinkan berlangsungnya pemekaran birokrasi yang hampir tak terkontrol. Akibatnya sama saja dengan era sebelumnya: korupsi.
Ide tentang penyempurnaan administrasi dan administrative reform itu berkembang sebagai bagian dari konsep administrasi pembangunan. Yang ke-tiga sebagai induknya akan kita bahas setelah ini, sedangkan yang pertama dan ke-dua dibahas pada bagian sesudahnya.
2. Administrasi pembangunan: menciptakan kesejahteraan
Pemikiran tentang administrasi pembangunan mulai masuk dan tumbuh di Indonesia pada tahun 1963, ketika Soekarno masih berkuasa dengan gaya etatisme melalui semboyan "demokrasi terpimpin"-nya. Gagasan ini sejak 1967 semakin dikembangkan, yakni ketika Soeharto sebagai pejabat sementara Presiden memilih untuk melakukan pembangunan yang terencana --bentuk lunak dari etatisme-- dan kemudian menjadikan pembanguan sebagai "ideologi" dan basis legitimasi utama pemerintahannya. Dari segi akademik konsep administrasi pembangunan kiranya merupakan perkembangan-lanjutan dari studi tentang perbandingan administrasi dan ekologi administrasi --yang merespons paradigma konsep dan prinsip umum administrasi serta ilmu administrasi fungsionil. Tokoh-tokoh pemikiran administrai pembangunan ini di Indonesia antara lain adalah Awaloedin Djamin yang pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja, Bintoro Tjokroamidjojo yang pernah mengepalai LAN dan Sondang P. Siagian --ketiganya sepertinya tidak tergantikan oleh penulis lain hingga tahun 2000 ini.
Pemerintahan Soeharto berusaha untuk mengoreksi kelemahan --untuk tidak menyebut kegagalan-- sistem liberal di satu pihak dan etatisme di pihak lain pada masa pemerintahan antara 1950 hingga 1965. Konsepnya adalah: dikembangkannya suatu sistem ekonomi pasar yang terencana dimana pemerintah merupakan unsur pembangunan (agent of development). Agen di sini mempunyai pengertian bahwa pemerintah bukanlah pihak yang (paling) menguasai kegiatan-kegiatan ekonomi melainkan merupakan organ yang mengarahkan, mengawasi, membimbing dan menggairahkan kegiatan ekonomi. Untuk itu pemerintah membuat rencana pembangunan dan mendekonsentrasikan pengambilan keputusan ekonomi kepada swasta. Dibandingkan dengan gagasan new public management, reiinventing government, lean government atau schlanker Staat, konsep administrasi pembangunan pada akhir 1960-an ini dapat dikatakan sudah sangat maju. Tetapi berbeda dengan negara-negara Amerika dan Eropa, dimana konsep new public management berkembang sejak awal 1980-an setelah pemerintah menyadari bahwa dirinya telah mulai terlalu aktif dan kemudian merasa tidak lagi berdaya untuk tetap aktif, di Indonesia sejak awal 1970-an konsep tersebut dikembangkan justru ketika pemerintah sedang memperoleh rejeki minyak yang memungkinkannya aktif bekerja sebagai aktor utama pembangunan. Akibatnya sekalipun gagasan itu tetap bertahan dan disebarkan dalam berbagai pendikan dan latihan (diklat) pegawai negeri, praktiknya adalah bahwa administrasi Indonesia berperan sebagai penguasa dan bukannya pengarah hingga paruh pertama 1980-an (lihat bab terdahulu).
Perkembangan gagasan administrasi pembangunan dapat dilacak awalnya dari tahun 1951 ketika PBB mengeluarkan buku kecil tentang standar dan teknik administrasi negara khususnya untuk keperluan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang. Tahun 1952 para ahli melakukan pertemuan dan menghasilkan laporan berjudul Outline of a Suggested Method of Study of Comparative Administration --mereka di kemudian hari terbentuk sebagai Comparative Administration Group (CAG) lalu berkembang menjadi Development Administration Group (DAG). Perhatuan utama dari organisasi ini adalah masalah-masalah administrasi di negara-negara sedang berkembang dalam konteks sosial, budaya , politik dan ekonomi mereka. Tahun 1961 PBB menyusun buku lagi berjudul A Handbook of Public Administration --Current Concepts and Practice with Special Reference to Developing Countries.
Dari pengalaman empiris negara-negara sedang berkembang, DAG merumuskan alat analisa untuk administrasi di negara-negara tersebut. Mereka kemudian merasakan adanya beberapa perbedaan antara konsep administrasi negara di negara-negara maju dengan administrasi negara di negara-negara yang sedang membangun, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1. Terlihat pada pembedaan ini bahwa apa yang disebut "administrasi pembangunan" bersifat sangat reformatif untuk mengejar tujuan-tujuan perubahan ke arah yang lebih "baik" pada khususnya dan untuk menanggapi situasi riil lingkungan pada umumnya.
Tabel 5.1. Perbedaan antara administrasi negara dan administrasi pembangunan.
Administrasi negara Administrasi pembangunan
- netral di hadapan masyarakat - mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat
- pelayanan publik dan efisiensi - inovasi
- agen penyeimbang - agen perubahan dan pembangunan
- legalistis, hukum dan ketertiban - ekologis, pemecahan masalah, orientasi pada
program
Sumber: Diringkas dari Tjokroamidjojo 1995, h. 9-10.
Dalam penjelasannya Tjokroamidjojo mengatakan, bahwa administrasi pembangunan tidak saja menghendaki administrasi kepegawaian yang rapi tapi juga memungkinkan diperolehnya pegawai yang berkualitas untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi pembangunan serta yang berorientasi kepada prestasi. Contohnya dalam hal ekspor, administrasi pembangunan tidak saja menghendaki tertibnya ekspor melainkan juga bergairahnya ekspor --dan ini seringkali mensyaratkan adanya perubahan sistem administrai yang beresiko kurang tertib dan kurang lancar untuk sementara waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adminitrasi pembangunan mengandung arti "pengadministrasian usaha-usaha pembangunan" di satu pihak dan "pembangunan sistem administrasi" di pihak lain.
Konsep administrasi pembangunan juga terkesan berusaha menjadi jalan tengah antara bentuk negara yang laissez faire dan welfare state. Pemerintah tidak membiarkan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri dan sebaliknya tidak juga menjadi abdi sosial, melainkan mendorong masyarakat untuk berkembang. Tetapi konsep ini tampaknya sulit dilaksanakan, dalam arti pemerintah di negara yang sedang berkembang cenderung memperluas kegiatannya, karena di negara tersebut hanya pemerintahlah yang memiliki potensi modernitas --tenaga terdidik, teknologi, sentuhan informasi dan penguasaan dana. Dan tampaknya memang dalam praktiknya konsep ini sulit dijumpai dalam bentuknya yang ideal. Apa yang diharapkan sebagai pemerintahan-tengah tidak terwujud, dan konsep administrasi pembangunan relatif tinggal angan-angan, jika bukannya konsep itu sendiri memang bersifat utopis. Hal ini diakui sendiri oleh Tjokroamidjojo, yang melihat bahwa negara-negara yang pada dasarnya laissez faire pun pada akhir 60-an cenderung untuk meningkatkan aktivitasnya di bidang pelayanan umum, apalagi di negara-negara yang sedang berkembang.
Konsep ini menjadi surut popularitasnya ketika praktik pembangunan di Indonesia mendapatkan kritik terutama karena terjadinya bias pembangunan ke Jawa, ke perkotaan dan ke lapisan yang mampu, sehingga menimbulkan jurang sosial yang sangat lebar antara kelompok kaya dan miskin di satu pihak, dan karena pembangunan terbukti dijadikan ideologi untuk melanggengkan kekuasaan dan menekan pertumbuhan demokrasi. Bahkan pada 1982 dua orang pengamat administrasi pembangunan telah melontarkan kritik mereka dalam istilah the paradox of development administration --pembangunan memerlukan sistem administrasi yang efektif, tapi sistem administrasi yang efektif menghambat pembangunan politik (baca: demokratisasi) yang akibatnya justru menjadikan sistem administrasi itu korup, yang mengakibatkan sistem administrasi itu boros, nepotis, tidak efektif, sehingga menciptakan distorsi pembangunan dan apa yang disebut "ekonomi biaya tinggi". (Lihat Gambar 5.1.) Nepotisme berlangsung secara meluas, dimana para pejabat instansi berusaha merekrut "teman-teman" mereka. Dan karena banyak pejabat yang melakukan ini, maka "ketenteraman dan keharmonisan" kerja di instansi tak dapat terjaga. Selain bias pembangunan, kritik terhadap praktik pembangunan juga diajukan terhadap prioritas kebijakannya, yakni terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (yang berdampak kesenjangan sosial) dan mengabaikan pembangunan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, apalagi dengan menguatnya kepedulian terhadap pencemaran lingkungan, sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan (pertumbuhan plus pemerataan atau redistribusi dan penghapusan kemiskinan, perhatian terhadap kualitas manusia dan lingkungan hidup) mulai dikenal.
Administrasi pembangunan seringkali terwujud sebagai "proyek pemerintah" dengan masyarakat sebagai obyeknya --yang tidak boleh menolak. Misalnya, "pembangunan pengusaha kecil" berarti dilakukannya pembinaan oleh banyak instansi pemerintah terhadap pengusaha kecil, sehingga para pengusaha itu justeru mengeluh karena teralalu sering dibina oleh instansi yang berbeda, yang memakan banyak waktu tapi dengan hasil yang tidak jelas. Contoh lain adalah di bidang kesehatan. Program-program pembangunan kesehatan dilancarkan buka karena masyarakat ingin sehat, melainkan karena memang pemerintah "harus" menjalankan program itu dan menjadikan masyarakat sebagai kliennya, sebagai "saluran bantuan obat yang memang harus disalurkan". Di berbagai pelosok desa dididik apa yang disebut kader sehat, buka karena mereka menghendakinya melainkan karena para birokrat lokal harus melakukan itu untuk membuat "laporan pembangunan kesehatan". Masyarakat tidak terlibat atau dilibatkan dalam perumusan program, aspirasinya tersumbat dan tidak berdaya. Mereka menjadi bersifat tergantung dan menggantungkan-diri kepada pemerintah, kehilangan daya kritis, pasif dan menunggu. Aktivitas pembangunan (dari dan oleh pemerintah untuk masyarakat) jadinya menawarkan proyek-proyek yang seringkali asing bagi masyarakat penerima, dan inilah yang tampaknya memupuk rasa frustrasi masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dan menyulut berlangsungnya banyak protes massal sejak 1992-an. Lebih dari itu, anehnya, pada tahun 1992 itu kemiskinan dan keterbelakangan masih tetap merupakan masalah paling nyata di pedesaan Indonesia, di tengah puja-puji Bank Dunia terhadap kesuksesan pembangunan Indonesia.
Oleh karenanya tampaknya patut dicurigai bahwa "administrasi pembangunan" seperti yang dipopulerkan oleh Tjokroamidjojo sedikit-banyaknya, sengaja atau tidak, berusaha atau minimal berdampak memberikan legitimasi-intelektual bagi pemerintahan Soeharto. Dengan kata lain, "administrasi pembangunan" sebenarnya tidak mengandung pengertian akademik baru kecuali tidak lebih dari penerapan "administrasi negara" dalam masyarakat yang dikategorikan sedang "membangun": nation building and socioeconomic progress, dimana persoalan-antara maupun -lanjutannya adalah the legitimacy of regime, growth with distributive justice, social impact of development and partizipation in the development, sedangkan strateginya adalah ekonomi pasar yang berencana. Artinya, kedua istilah ini hanya berbeda dalam lokus-nya sedangkan persoalan fokus- (konseptual)nya adalah sama saja. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnyalah administrasi pembangunan merupakan suatu bentuk reformasi administrasi guna menanggapi tantangan negara yang sedang berkembang.
3. Penyempurnaan administrasi: mengejar efektivitas dan efisiensi
Pada tahun ke-tiga pemerintahan-transisionalnya Soeharto mengangkat seorang menteri negara untuk penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara (MENPAN) yang sekaligus menjadi ketua dari Proyek Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintahan. Proyek ini, yang dikenal dengan nama "Proyek 13", pada 1969 diganti menjadi "Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P)" yang bertugas menyempurnakan aparatur pemerintah agar mampu melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) dengan baik --suatu sistem perencanaan negara yang diterapkan sejak 1969 hingga setidaknya 1999. Melihat program-programnya, visi dari MENPAN sangat menyeluruh, mencakup dua program besar, yakni organisasi (struktur dan prosedur) dan personalia, dengan sasaran baik pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, perusahaan negara maupun perwakilan RI di luar negeri.
Pada 1973 kata MENPAN diberi pengertian yang lain: Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan sejak 1974 (hingga 1989) merangkap sebagai Wakil Ketua BAPPENAS --Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Istilah yang kemudian gemar diucapkan pada lima tahun berikutnya adalah: keserasian, keselarasan, keteraturan, kebulatan dan kemantapan. Pada masa ini, tepatnya sejak 1977, diberlakukan apa yang disebut "operasi tertib" (Opstib) untuk menindak mereka yang melakukan korupsi --khususnya pemerasan dan pungutan liar (pungli). Sama dengan sebelumnya, kebijakan Menpan diarahkan pada semua aspek administrasi: kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan. Kebijakan ini dilanjutkan pada periode lima tahunan berikutnya (Pelita III, dari 1979 hingga 1984). Pada periode ini penataan organisasi di Daerah dilakukan dengan empat sasaran:
- Penegasan susunan organisasi Pemerintah Daerah,
- Tugas dan wesenang tiap unit organisasi serta tata-kerja dan tata-hubungan-kerjanya,
- Peningkatan fungsi lembaga sosial yang ada di Daerah dan
- Penerapan secara serasi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Karena dianggap bahwa pengawasan oleh instansi-instansi pengawasan telah dapat berfungsi dengan baik, pada pertengahan Pelita III Opstib dihentikan. Sekalipun begitu toh diperlukan lembaga pengawas baru yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1983 yang merupakan perluasan dari Ditjen Pengawasan Keuangan Negara. Sejak 1984 (awal Pelita IV) MENPAN berubah arti menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Perubahan ini dikarenakan fungsinya tidak lagi melakukan tindakan yang operasional melainkan lebih pada pembinaan kebijakan-kebijakan di bidang aparatur negara.
Sejak 1989, awal Pelita V, aktivitas MENPAN terkesan lebih meningkat. Untuk pertama kalinya "peran serta masyarakat dalam pembangunan" mulai disebut secara khusus, setelah dua puluh tahun aktivitas "pembangunan" meletakkan masyarakat sebagai obyek. Pemerintah berusaha untuk "memantapkan perilaku birokrasi sehingga lebih menunjang prakarsa dan peran serta masyarakat". Kecuali itu perkembangan yang sangat penting adalah diintrodusikannya peradilan tata usaha negara. Sekalipun tidak dapat dinilai sangat efektif, dalam praktiknya kemudian introduksi ini meningkatkan posisi-tawar masyarakat terhadap birokrasi yang sewenang-wenang. Dalam perspektif yang luas hal ini merupakan sebuah langkah positif bagi proses demokratisasi. Dari sudut yang lain ini dapat dipandang sebagi orientasi birokrasi kepada masyarakat yang lebih tinggi, apalagi ditambah dengan adanya program penyederhanaan tatalaksana pelayanan umum. Hingga 1994 disusunlah apa yang disebut program pemacu dan program penyangga di sektor pendayagunaan aparatur negara. Program pemacunya ada delapan buah, yakni:
- Pengawasan melekat (Waskat, sejak 1983, dipertegas lagi dengan penataran sejak 1989),
- Analisis jabatan,
- Penyusunan jabatan fungsional,
- Peningkatan mutu kepemimpinan,
- Penyederhanaan prosedur kepegawaian,
- Penyederhanaan tatalaksana pelayanan umum,
- Perancangan sistem informasi administrasi pemerintahan,
- Penitikberatan otonomi Daerah di Kabupaten.
Sedangkan program pendukungnya ada sepuluh buah, yakni:
- Peningkataan kesejahteraan pegawai,
- Pemurnian pembinaan pegawai,
- Perampingan birokrasi,
- Manajemen administrasi pemerintah,
- Pemasyarakatan budaya kerja (sejak 1991, untuk menunjang Waskat),
- Pembentukan unit swadana,
- Penyelenggaraan peradilan tata usaha negara,
- Pemanfaatan bantuan hibah konsultan asing Asia,
- Penyeberluasan pemantapan manajemen kantor,
- Pengembangan program-program PAN di Daerah.
Sebagian dari program "pemacu" di atas terlihat kurang begitu konsisten dengan program "pendukung". Penyederhanaan tatalaksana pelayanan umum sebagai "pemacu" kiranya sama dengan perampingan birokrasi dalam program "pendukung". Selain itu penerapan peradilan tata usaha negara kiranya lebih layak disebut program pemacu dibanding program pendukung. (Pada tahun 1997, yakni empat tahun kemudian, seorang pejabat MenPAN pada sebuah seminar menata-ulang urutan program itu menjadi sebagai berikut:
- percontohan otonomi Dati II,
- perampingan organisasi,
- kebijakan zero growth,
- pemantapan sistem pembinaan karir pegawai,
- model pelayanan umum dan
- pemadatan hari kerja.)
Sukarno melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pemacu di atas, yang beberapa di antaranya disinggung di sini. Pengawasan melekat menurutnya belum menunjukkan keberhasilan fisik yang mampu meningkatkan mutu manajemen. Dia menyebut Keputusan Menpan No. 4 Th 1991 tentang budaya keja merupakan penguat bagi pengawasan melekat ini. Di dalamnya terpadukan konsep experiential learning dan total quality management untuk perbaikan manajemen. Program analisis jabatan telah melatih 8.000 orang pegawai di seluruh Indonesia, tapi ternyata mereka belum bisa memanfaatkannya untuk melakukan perencanaan kepegawaian, pendidikan dan latihan ataupun merumuskan jabatan fungsional secara lebih tepat. Karena itu perlu dilakukan perubahan format dan metode analisis jabatan menjadi lebih sederhana. Sementara itu dalam penyederhanaan tatalaksana pelayanan umum belum banyak dijumpai kemajuan. Menurut Sukarno pihak MenPAN telah melakukan pengkajian, inventarisasi data, memberikan anjuran dan melakukan inspeksi mendadak, tetapi ini tidak efektif. Hal ini menyangkut peraturan perundangan yang mengatur prosedur di satu pihak dan --yang lebih mengemuka-- sikap-perilaku pegawai di pihak lain.
Program pemacu yang terakhir adalah penitikberatan otonomi pada Kabupaten. Apa yang diidealkan oleh Sukarno, bahwa mulai 1995 (Pelita VI) keseimbangan pengurusan Pusat-Daerah sudah terwujud, ternyata belum. Penataran tentang UU No. 5 Th. 1974 tentang pemerintahan daerah telah dilakukan, telah dibentuk DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yang berisi Depdagri, Departemen lain, pemerintah-pemerintah Daerah dan MenPAN serta LAN sebagai pihak netral, tapi hasilnya belum terasa. Departemen teknis, menurut Sukarno, masih beranggapan bahwa Pemda merupakan bawahan Depdagri, sehingga mereka enggan mendesentralisasikan urusannya kepada pemerintah Daerah.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak dasawarsa pertama kemerdekaannya pemerintah Indonesia telah menyadari perlunya mengadakan perubahan administrasi. Tetapi keinginan untuk menciptakan sistem administrasi yang rasional, sederhana dan efisien ternyata tidak terwujud dengan baik. Penyebab yang dapat diduga adalah, pada dua dasawarsa pertama, kehidupan politik-administrasi yang masih kuat diwarnai spoil system dan, pada tiga dasawarsa sesudahnya, sistem politik yang otoritarian memang memberikan perhatian yang memadai pada perbaikan sistem administrasi, namun karena birokrasi merupakan aktor tunggal dalam pembangunan dan kecuali itu dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengontrol masyarakat maka usaha perbaikan administrasi terkalahkan oleh dan tenggelam dalam pembengkakan birokrasi (parkinsonisme) dan korupsi serta penyalahgunaan wewenang lainnya. Ketika pada awalnya Soeharto berusaha untuk menjadikan pegawai negeri netral dari pengaruh politik, pada akhirnya pegawai negeri menjadi anggota partai Golkar dan karirnya seringkali lebih banyak ditentukan oleh prestasinya dalam partai tersebut. Ini kiranya merupakan ironi, karena salah satu legitimasi pemerintahan Soeharto adalah teknokratisme --yang mensyaratkan birokrasi rasional.
Sementara itu dalam hal pemberian wewenang yang lebih besar kepada Kabupaten ada dua hal yang perlu dikomentari. Pertama, "kelambatan" ini mungkin tidak disebabkan oleh masalah teknis seperti disinyalir Sukarno, melainkan karena secara politis belum dirasakan urgensinya. Disatu pihak pemerintah Soeharto masih memiliki dana yang memadai untuk membiayai kegiatan birokrasinya dan di pihak lain tidak ada tekanan yang berarti dari dunia internasional terutama negara donor untuk melakukan desentralisasi ini. Bahwa pada awal 1990-an kepedulian terhadap desentralisasi ini menguat membuktikan dugaan ini, yakni tatkala dana pemerintah berkurang dan terutama tekanan negara donor menguat. (Lihat bab terdahulu.)
Mencoba merumuskan visinya, Sukarno melihat perlunya dilakukan beberapa tindakan untuk memperbaiki mutu pelayanan umum:
- Keterbukaan dan kemudahan prosedur,
- Penetapan tarif yang jelas dan terjangkau,
- Keterampilan aparatur dalam teknik pelayanan,
- Penyediaan penampungan keluhan masyarakat,
- Penciptaan sistem pengawasan berganda terhadap pelaksanaan prosedur dan
- Pemasyarakatan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Visi pelayanan seperti ini tampaknya mendapat pembenaran dari banyak kalangan. Banyak instansi mulai tertatih-tatih untuk memperbaiki kualitas pelayanannya: menuju proses administrasi yang sederhana dan cepat. Tapi kegiatan ke arah itu belum berlangsung secara meluas, hingga akhirnya setelah terjadi Gerakan Reformasi Mei 1998 yang melengserkan Soeharto barulah birokrasi membuka diri untuk memulainya. Salah satunya adalah Kotamadya Malang yang membangun suatu sistem pelayanan satu atap yang menyerupai Bürgerbüro di Jerman, dinamai UPMT (Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu). "Bürgerbüro" yang dibuat sejak 1998 ini menyatukan sebanyak 32 jenis layanan (dhi. ijin dan surat keterangan) dari beberapa instansi di sebuah gedung. Efeknya bukan hanya penyatuan fisik melainkan juga mendorong tiap pegawai yang mewakili instansinya untuk bekerja lebih cepat, menjadikan proses pelayanan lebih transparan sehingga masyarakat dapat mengontrolnya dan ada kepastian waktu pengerjaan layanan. Tapi berbeda dengan Bürgerbüro di Jerman dimana setiap pegawai mengerjakan setiap hal, dalam biro ini seorang pegawai bekerja mewakili instansinya masing-masing. Unit semacam ini tampaknya telah mulai dirintis oleh beberapa kabupaten sejak 1995, yakni bersamaan dengan diperkenalkannya proyek percontohan otonomi kabupaten, dan diinspirasii oleh SK MenPAN No. 81/1993 tentang pedoman tata-laksana pelayanan umum.
Apakah sistem pelayanan satu atap itu telah dijadikan oleh pemerintah Indonesia sebagai cita-cita? Tidak ada jawaban-persis yang dapat diberikan. Hanya saja jika kita melihat daftar masalah adminsitrasi yang dibuat oleh Tjokroamidjojo dan arahan dari penyempurnaan administrasi yang disusun oleh dua orang penulis lain di bawah ini, dapat diduga bahwa biro semacam inilah yang diidealkan oleh pemerintah. Daftar berikut ini memberikan penekanan yang besar terhadap efisiensi di satu pihak dan kualitas pelayanan masyarakat di pihak lain.
Masalah administrasi di Indonesia menurut Tjokroamidjojo adalah atau terletak pada hal-hal sebagai berikut:
- orientasi kepada status lebih besar daripada orientasi kepada prestasi,
- menonjolnya hubungan pribadi dalam rangka hubungan kerja,
- penyampaian laporan yang baik dan bukannya yang benar,
- sikap legalistis birokrasi,
- koordinasi, komunikasi intern dan pengawasan yang buruk,
- sikap lama penjajahan dan mental etatisme,
- struktur, kualitas dan penyebaran pegawai,
- lebih bersihnya pelaksanaan pemerintahan,
- jam kerja dan sistem gaji,
- motivasi dan produktivitas,
- etika, jiwa korsa dan pengabdian,
- orientasi pelayanan,
- entrepreneurial,
- orientasi keadilan,
- sistem dan proses politik,
- geografi dan masalah persatuan nasional,
- struktur pasar,
- struktur penduduk.
Selanjutnya dikatakan bahwa penyempurnaan administrasi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan administrasi negara yang bersih: bebas dari penyelewengan dan penyimpangan atau korupsi pada umumnya yang mengakibatkan pemborosan. Dua tindakan yang perlu dilakukan bersamaan adalah: menyempurnakan pengawasan di satu pihak dan meningkatkan kesejahteraan pegawai di pihak lain, kecuali itu perlu disusun manual prosedur dan persyaratan yang diketahui bersama oleh pihak birokrasi dan pengguna jasa. Mengutip Hahn Been Lee dan Samonte (1970) dikemukakan lima alat ukur usaha penyempurnaan administrasi negara sebagai berikut:
- penekanan yang baru terhadap program,
- sikap dan perilaku yang diperbaiki terhadap klien dan anggota birokrasi,
- perubahan dalam gaya internal administrasi ke arah manajemen yang komunikatif dan partisipatif,
- penekanan yang lebih kuat lagi terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya,
- dikuranginya penekanan terhadap hal-hal rutin dan legalistik.
4. Reformasi administrasi: menghapus otokrasi
Ide-ide reformasi administrasi, seperti terlihat di atas, telah mulai muncul sejak tahun 1970-an, berbarengan dengan konsep administrasi pembangunan. Sekitar satu dasawarsa kemudian konsep reformasi memperoleh rumusan yang jelas, misalnya oleh G.E. Caiden, tapi baru masuk ke Indonesia secara relatif meluas sejak awal 1990-an. Menurut ide itu, reformasi administrasi dapat terwujud dalam lima bentuk, yaitu: (a) munculnya inisiatif, upaya dan agensi publik, (b) proses administrasi yang menjadi sederhana melalui reorganisasi, redistribusi dan konsolidasi, (c) berkurangnya pengaturan (deregulasi), (d) berkurangnya prosedur yang berlebihan (debirokratisasi), dan (e) hubungan birokrasi kepada publik sebagai pelayan dan bukan sebaliknya. Dari sudut pandang lain, istilah "reformasi administrasi" menunjuk pada peristiwa perubahan struktur dan prosedur (dan akibatnya teknik dan budaya) administrasi guna menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungannya.
Menurut pengertian ke-dua di atas, per definisi setiap organisasi negara pastilah dan haruslah mengadakan reformasi setiap saat. Negara RI pun, seperti diuraikan di depan, selalu mengadakan reformasi sejak berdirinya, dimulai dengan apa yang disebut "rasionalisasi" (pengurangan jumlah pegawai, perampingan struktur). Selanjutnya dalam diskurus tentang administrasi pembangunan sejak awal 1970-an reformasi administrasi merupakan salah satu temanya. Namun tema ini dalam wacana publik Indonesia kurang begitu populer, hingga pada 1984 mulai dipakai ketika singkatan MENPAN mendapat arti baru, dari Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1969) menjadi Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (1973) hingga Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (1984). Pendayagunaan yang berarti "peningkatan efektivitas" menghendaki dilakukannya perubahan atau reformasi administrasi. Bersamaan dengan itu tuntutan liberalisasi global di satu pihak dan berkurangnya anggaran pemerintah pada awal 1980-an memaksa pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Kemudian sejak awal 1990-an, bersamaan dengan diskursus tentang desentralisasi pemerintahan atau otonomisasi Daerah (lihat bab terdahulu, istilah reformasi administrasi mulai lebih sering digunakan. Penyebutan istilah reformasi administrasi biasanya dikaitkan selain dengan tantangan globalisasi pada abad ke-21 juga dengan tuntutan demokratisasi dan perkembangan sosial ke arah masyarakat industri dan informasi, yang semuanya mempengaruhi tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan pemerintah.
Dinyatakan oleh Sukarno, misalnya, bahwa di masa depan teknologi informasi akan begitu maju yang memungkinkan dilakukannya paperless administration (administrasi tanpa kertas). Tetapi anehnya, semua program MENPAN pada 1993 kecuali dua program yang terakhir berikut ini masih berkutat pada masalah-masalah lama, yakni: manajemen kantor, klasifikasi jabatan, prosedur kepegawaian, mutu kepemimpinan, sistem informasi administrasi, pengawasan melekat, pelayanan masyarakat dan pengembangan kemampuan Daerah. Sementara Maret 1993 Presiden masih menekankan lagi perlunya pelaksanaan manajeman modern dengan enam indikator: perencanaan matang, pelaksanaan tepat, pengawasan ketat, terkoordinasi, terintegrasi, sinkron. Ini menandakan bahwa masalah-masalah organisasi "klasik" semacam itu ternyata belum terkelola dengan baik selama lebih dari duapuluh tahun pemerintahan Soeharto, yang di dalamnya selalu diucapkan istilah administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Pernyataan Presiden itu juga menunjukkan pengakuan, bahwa dalam sistem politik dan administrasi yang monolitik selama Orba ternyata pimpinan administrasi tidak mampu menjamin koordinasi kerja di antara berbagai departemen dan apalagi menjamin efektivitasnya. Tesis awal Orba bahwa stabilitas politik dan demokrasi yang terbatasi akan mampu menjamin administrasi yang efektif ternyata tidak menemui bukti konkritnya di Indonesia. Sementara itu dari sisi pandang lain, daftar program MENPAN tadi barangkali menunjukkan bahwa MENPAN tidak mampu, jika bukannya tidak berani, mempertajam skala prioritas programnya pada dua yang terakhir saja, yakni peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dan desentralisasi pemerintahan atau otonomisasi Daerah.
Diskursus tentang reformasi pada awal 1990-an itu juga merujuk Taiwan dan Korea Selatan sebagai bandingan bagi Indonesia dalam hal status industrialisasi mereka. Dikatakan bahwa industrialisasi yang berhasil di kedua negara itu terbukti menjadikan tuntutan akan demokrasi yang lebih tinggi, karena organisasi masyarakat semakin terproliferasi (tidak terpusat sebagaimana dalam masyarakat agraris tradisional), dan selain itu bersama-sama dengan kemajuan teknologi informasi dan munculnya generasi baru industrialisasi itu juga mendorong proses civilization yang lebih cepat. Oleh karena itu reformasi administrasi harus diarahkan pada pemberian kesempatan bagi partisipasi masyarakat melalui keterbukaan mekanisme pemerintahan, deregulasi dan desentralisasi serta pemerataan kesempatan berusaha dan kompetisi yang adil namun dibarengi dengan proteksi terhadap mereka yang masih lemah.
Tampaknya deregulasi dan debirokratisasi itulah yang menjadi tujuan dari reformasi administrasi sebagaimana diinginkan oleh banyak pakar. Artinya pemerintah harus mengakaji-ulang perannya dalam penyediaan pelayanan publik, untuk kemudian menyerahkan sebagian besar peran itu kepada swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain karena krisis anggaran pemerintah, juga pada dasarnya karena masyarakat sejak dulu telah melakukan pemenuhan-sendiri kebutuhan-kebutuhan mereka, baik mandiri maupun melalaui organisasi sosial seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Gereja. Karenanya pemerintah perlu melakukan kemitraan dengan swasta dan LSM itu --berbagi tanggungjawab dalam penyediaan pelayanan publik. Selain bekerjasama, kemitraan ini dapat pula bersifat kompetitif: pemerintah dan swasta menyediakan pelayanan publik yang sama, dan mereka yang lebih "baik"-lah yang harus dibiarkan untuk berjalan terus. Dengan kompetisi semua pihak akan terdorong untuk meningkatkan daya-tanggap, kualitas dan efisiensi pelayanannya. Masing-masing dapat belajar dari yang lainnya, terutama pemerintah yang akan terdorong untuk belajar nilai-nilai kewirausahaan dari swasta.
Jika visi di atas dapat berjalan, maka pemerintah akan berperan tidak terutama sebagai penyedia pelayanan publik melainkan terkonsentrasi pada: menetapkan agenda dan prioritas pelayanan publik, menentukan standar performans, memonitor hasil kerja dan memberikan insentif serta sanksi pada para penyedian layanan publik itu. Namun harus dicatat, bahwa pengalihan peran pemerintah kepada swasta itu harus belangsung secara transparan, agar supaya berlangsung kompetisi yang sehat di antara swasta sendiri dan agar tidak terjadi kolusi antara pemerintah-swasta yang biasanya akan merugikan masyarakat pengguna layanan. Untuk menjamin transparansi ini kontrol dari birokrasi dari level yang lebih tinggi, kontrol politik dan kontrol masyarakat harus diusahakan untuk dapat berlangsung dengan lancar. Dengan kata lain, masyarakat harus diberdayakan, daya kritis mereka harus dibiarkan untuk berkembang, karena kalau tidak --sebagaimana pembangunan top-down yang bias kepada lapisan mampu-- privatisasi sebagai pilihan reformasi juga berpotensi untuk menjadikan pelayanan pubil bias kepada mereka yang kaya juga. Dalam konteks inti dari reformasi adalah bahwa birokrasi mendorong munculnya inisiatif, karsa dan upaya masyarakat sendiri.
Jadi, seperti ditunjukkan dalam bab sebelumnya, ketika dari kepentingan pemerintah, reformasi (deregulasi dan debirokratisasi) perlu dilakukan karena kondisi finansial Negara yang memburuk, dari kepentingan masyarakat, reformasi (desentralisasi dan demokratisasi) diperlukan karena selama ini masyarakat telah "dimatikan" oleh pemerintah. Dalam batas tertentu, hal ini merupakan paradoks lain dari pembangunan: ketika pada awalnya pemerintah "menstabilkan" masyarakat untuk pasif menerima aktivitas pembangunan oleh pemerintah, pada akhirnya masyarakat mengalami mobilitas sosial berupa "kemajuan-kemajuan" dalam hal tingkat pendapatan, tingkat melek huruf, tingat sentuhan terhadap media massa dan juga tingkat urbanisasi, dan ini semua berbalik menjadi "bumerang" bagi pemerintah yang didesak untuk membebaskan masyarakat dari intervensinya yang berlebihan (lihat Gambar 5.2). Selama pemerintah aktif melancarkan program pembangunan masyarakat telah berkembang sehingga memiliki kesadaran dan kemampuan politik yang lebih tinggi, muncul kelas menengah yang independen, sehingga artikulasi politik masyarakat lebih kuat, memunculkan desakan kepada pemerintah untuk menjamin hak-hak sipil seperti kebebasan pers dan berorganisasi.
Jadinya reformasi administrasi di Indonesia semestinya diarahkan kepada dua aspek. Pertama, secara internal reformasi administrasi hendaknya diarahkan pada usaha memantapkan pembangunan nilai-nilai birokrasi modern (tindakan organisasi yang rasional, efisien, legal, pasti dan terukur, serta sikap pegawai yang disiplin, tekun, teliti, cermat, bersemangat dan berorientasi pada prestasi) guna mencabut nilai-nilai tradisional, feodal, patrimonial dan aristokratik (tindakan atau keputusan organisasi yang bersifat personal, lisan, tak pasti, tak terukur serta sikap pegawai yang yang tak disiplin, malas dan minta dilayani). Budaya malu harus diganti dengan budaya bersalah, hal-hal ritual yang terwujud secara ekstrem sebagai theatrical state hendaklah dikurangi ke arah hal-hal yang substansial. Di pihak lain yang tak terlepas dari aspek ini, ke-dua, secara eksternal reformasi administrasi harus diarahkan pada usaha untuk menjamin berlangsungnya demokrasi perumusan kebijakan publik dalam suatu masyarakat industri, teknologi dan informasi. Fungsi birokrasi sebagai pangreh pradja (abdi negara yang mengatur masyarakat, memaksa dan wajib ditaati) hendaknya diganti menjadi sebagai pamong pradja (abdi masyarakat yang melayani kebutuhan publik bersama-sama dengan publik itu sendiri), hubungan pemerintah-masyarakat yang patron-klien hendaknya diganti dengan hubungan yang sederajat dalam suatu civil society.
Namun kehati-hatian harus diterapkan dalam hal yang pertama. Ialah bahwa tidak semua nilai tradisional harus dibuang, bahkan mereka dapat dipandang bukan sebagai kendala dan hambatan yang perlu disingkirkan melainkan justru sebagai cultural resources. Nilai-nilai paternalisme dan solidaritas sosial yang kuat, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi massa guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang "baik", budaya malu dapat ditransformasikan alat kontrol yang baik bagi birokrasi. Sementara itu nilai-nilai priyayi yang positif, seperti tekun, loyal, integritas pribadi dan keluhuran budi pun dapat dipertahankan dan dikembangkan, sebagaimana di Jepang nilai-nilai tradisionalnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Nilai-nilai tradisional Jepang itu adalah familiisme (tempat kerja dianggap sebagai milik keluarga sendiri, yang kepadanya seorang pegawai mempersembahkan hampir seluruh komitmennya) dan akibatnya kesetiaan seumur hidup kepada tempat kerja (sangat jarang terjadi perpindahan bidang atau tempat kerja), gerontokrasi (senioritas sangat dihargai) dan penghormatan pada konsensus (pembagian kerja tidak kaku).
5. Pembaharuan (modernisasi) administrasi: menyambut globalisasi
Pada Mei 1995 PERSADI (Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia) menyelenggarkaan sebuah seminar untuk mengawali konggresnya yang ke-tiga. Organisasi yang para pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah ini, waktu itu diketuai Mustopadidjaja AR, staf senior Bappenas, berusaha untuk merumuskan kembali model administrasi negara RI yang terbaik untuk menghadapi apa yang disebutnya era globalisasi dan informasi. Mengingat karakteristik anggotanya, Persadi membuat butir-butir rekomendasi yang secara "bahasa" lunak, yakni pembaharuan atau modernasisasi. Kedua istilah ini sebenarnya bukan barang baru, karena keduanya telah menjadi inti dari gerakan pembangunan, namun isi rekomendasi itu relatif progresif: mengurangi intervensionisme pemerintah selama era pembangunan sebelumnya. Pengurangan intervensi ini pun bukan barang baru, karena deregulasi dan debirokratisasi telah dimulai oleh pemerintah pada 1983, ketika terjadi krisis penurunan harga minyak. Jadinya ide-ide yang berkembang hanyalah penekanan dari ide sebelumnya, presentasi dengan bahasa yang berbeda, jika bukannya --secara tidak langsung-- berusaha mengevaluasi dan mengritik ketidakberhasilan pemerintah selama masa sebelumnya dalam merealisasi ide-idenya sendiri. Berikut ini pemikiran yang terumuskan dalam seminar.
Seminar yang bertema "Modernisasi Administrasi Menghadapi Globalisasi Menyukseskan PJP-II" itu memanfaatkan pidato Presiden empat sebelumnya di Bogor dalam pembukaan penataran P4 bagi para pejabat eselon I sipil maupun militer sebagai rujukannya. (Melihat isinya, pidato ini tampaknya dipersiapkan oleh para pengurus Persadi sendiri.) Pidato di bulan Januari itu diucapkan setelah pada bulan Nopember tahun sebelumnya di kota yang sama berlangsung konferensi APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation). Pada penataran P4 yang dilakukan enambelas tahun setelah penataran P4 yang pertama 1978 itu ditegaskan perlunya kesadaran akan munculnya zaman baru: kehidupan akan semakin terbuka karena arus informasi menjadi begitu cepat (sarananya adalah radio dan televisi, belum disebut adanya internet) dan akan terbentuk rezim perdagangan bebas dunia. Dalam zaman baru ini tugas negara yang utama berubah menjadi hanya penyedia sarana-sarana "utama" dan --yang lebih penting-- pemberi arah, pencipta peluang, pemberi dorongan dan pengayom berlangsungnya prakarsa dan kreativitas masyarakat. RI sebagai negara kesatuan hanya akan merasa berkewajiban menjaga kesatuan politik, moneter, diplomasi dan pertahanan-keamanan, sedangkan masyarakat akan dibiarkan mandiri lewat pemberian otonomi dan desentralisasi maupun deregulasi dan debirokratisasi yang telah dilakukan sejak 1983.
Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas dunia, dimulai dari level AFTA (Asean Free Trade Agreement) sejak 2003, APEC sejak 2010 dan dunia (lewat WTO, World Trade Organisation) sejak 2020. Perdagangan dunia yang bebas ini "mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap" harus kita masuki, dan kita tidak perlu risau, karena "bangsa kita adalah bangsa wiraswasta, yang terbiasa merantau berlayar dan berniaga ke negeri-negeri yang jauh." Hanya saja, karena semua itu bisa mengarah kepada liberalisme, perlu dikembangkan model-model kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan sedang sesuai dengan asas kekeluargaan. Selain itu masyarakat harus siap secara teknis dan profesional, disamping secara ideologis, politis, ekonomis dan sosial budaya. Daya saing masyarakat dan Negara harus ditingkatkan, dimana pada pihak Negara harus dilakukan perubahan organisasi, prosedur, tata-kerja dan peraturan perundang-undangan.
Merujuk pada pidato Presiden itu, Tjokroamidjojo menyebut perlunya pengalihan sistem ekonomi masyarakat, dari public sector led menjadi private sector led economy, apalagi jika diingat berkurangnya dana dari minyak. Administrasi, baik negara maupun swasta, jadinya dituntut untuk lebih efisien, produktif dan inovatif. Mereka perlu melakukan moderniasi: pembaharuan administrasi untuk beradaptasi dengan realitas baru di bidang politik, ekonomi dan sosial. Sekalipun terkesan adanya penekanan terhadap perlunya pengurangan peran pemerintah atau empowering rather than serving, Silalahi (Menpan) masih menganggap perlu memperluas pelayanan pemerintah di bidang tertentu selain meningkatkan kualitasnya, dan --sayangnya-- antara perluasan dan peningkatan kualitas itu seringkali dijumpai dilema. Dicontohkannya pelayanan listrik: sebaiknya diperluas ke masyarakat desa yang tidak produktif, atau dikonsentrasikan di daerah industri saja? Administrasi, karenanya, oleh Moerdiono (Mensesneg) dimaknai sebagai "kemampuatn kreatif untuk merakit serta mendayagunakan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan." Menurutnya, selama ini belum pernah ada literatur administrasi yang membahas konsep dan kiat manajemen proses transformasi dalam skala nasional. Terobosan di bidang administrasi seringkali disumbangkan oleh ekonom, usahawan, politisi maupun pemikir militer. Oleh karenanya, disamping perlu belajar dari pengalaman negara lain, khazanah pengalaman bangsa sendiri perlu disistematisir sebagai bahan pelajaran yang berharga.
Sedikit berbeda dengan pidato Presiden yang menekankan adanya perubahan kualitas kehidupan sehingga diperlukan adanya perubahan sistem administrasi, Moerdiono justru menyatakan bahwa perubahan sistem administrasi bersesuaian dengan konsep pembangunan yang dicanangkan pada awal 1970-an, dimana setelah berlangsung "akselerasi modernisasi 25 tahun" bangsa Indonesia akan memasuki tahap "tinggal landas" --melanjutkan pembangunan dengan kekuatan sendiri. Inilah yang tampaknya dimaksudkan oleh Moerdiono sebagai latarbelakang dari deregulasi dan debirokratisasi sejak 1983 dan percobaan otonomi kabupaten sejak 1995. (Otonomisasi diartikannya sebagai pelimpahan wewenang, personil, perlengkapan dan dana kepada kabupaten.)
Kartasasmita (Ketua Bappenas) melihat perlunya pembaharuan sistem administrasi karena alasan yang lebih pragmatis: mesin perekonomian Indonesia ternyata telah berjalan secara tidak mulus --tidak efisien, sering tersendat-sendat dan boros. Pertumbuhan ekonomi selalu disertai oleh inflasi yang tinggi, dan ini semua mengakibatkan kesenjangan struktural alias ketidakadilan: sedikit pengusaha besar menguasai sangat banyak aset produktif --modal, tenaga terampil, teknologi dan akses pasar. Pada 1992 sejumlah 97,4 persen (yakni 32,6 juta) dari seluruh perusahaan dan usaha rumah tangga memiliki omzet, output atau sisa hasil usaha kurang dari Rp 50 juta. Implikasinya adalah bahwa proses tinggal landas tidak akan mungkin berjalan serempak di seluruh tanah air. Kesenjangan itu harus dihentikan. Dalam waktu dekat ekonomi tradisional harus sudah masuk ke ekonomi modern, ekonomi subsistensi menjadi ekonomi pasar, dan ketergantungan menjadi kemandirian.
Dalam konteks itu, "demokrasi ekonomi" mulai diperbincangkan lagi. Pasal 33 UUD 1945 dirujuk, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Konsep "kemitraan" segitiga diperkenalkan, yakni antara pengusaha besar - pengusaha menengah dan kecil - pemerintah, dengan pemerintah sebagai aktor yang memegang peran aktif. Kemitraan atau organized market dirumuskan sebagai hubungan kerja sinergis yang saling menguntungkan (bukan program karitas) antar pelaku ekonomi, baik dalam bidang permodalan, produksi maupun distribusi, juga antar-sektor dan -daerah Ini semua dimaksudkan untuk menghindarkan persaingan yang tidak sehat yang cenderung mengarah ke monopoli, dan memang konsekeunsinya harus dihilangkan orientasi pada economies of scale.
Dengan rumusan yang berbeda, Mustopadidjaja menyebut demokrasi ekonomi sebagai suatu sistem ekonomi yang tidak free figt liberalism di satu pihak dan tidak etatisme di pihak lain, tidak ada monopoli dan monopsoni, yang ada hanyalah keadilan sosial. Intinya: jalan tengah. Liberalisme ternyata telah menghasilkan pemusatan kekuata ekonomi, ketimpangan lokasi investasi, lemahnya posisi tawar pengusaha kecil dan menengah, dan akibatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu etatisme yang berbentuk penguasaan dan pengendalian langsung oleh pemerintah terhadap sistem produksi dan distribusi terbukti menghasilkan dampak birokratisasi, korupsi, in-efisiensi, inflasi dan degradasi kesejahteraan. Lewat jalan tengah diharapkan terjadi transaksi bisnis yang sehat, terbuka dan efisien, sehingga pemerataan dan pertumbuhan yang berkeadilan dapat terwujud. Dengan kata lain: kita dapat ikut dalam arus liberalisasi perdagangan tanpa harus terjebak pada liberalisme. Demokrasi ekonomi ditandai oleh lima hal:
- mekanisme pasar dan keterkaitan pasar domestik dengan pasar regional dan internasional,
- intervensi pemerintah,
- hak inisiatif dan hak budget DPR,
- hak milik perorangan dan pemanfaatannya, peran aktif warga negara dalam kegiatan ekonomi,
- pengawasan legislatif dan sosial.
Hal-hal apa yang (masih) perlu dibenahi? Yang terutama adalah rendahnya tingkat efisiensi yang mengakibatkan rendahnya daya saing negara di pasar internasional. Teknologi informasi perlu diadopsi guna memperbaiki manajemen, mengubah administrasi yang konvensional menjadi administrasi modern, dari legalisasi menjadi efisiensi dan pelayanan. Dalam kaitannya dengan pelayanan, sikap dan perilaku pegawai perlu diubah, sehingga tidak "senang dan merasa bangga melihat masyarakat yang dilayani menunggu lama...bahkan untuk kepentingan negara, misalnya (dalam pembayaran) pajak...(dan) langganan listrik". Pegawai negeri harus bersikap pro-aktif, dan sekalipun berada dalam birokrasi harus meninggalkan sikap-sikap yang birokratis. Ini terkait dengan tingkat kesejahteraan mereka. Untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan pegawai, pemerintah tidak perlu menambah pegawai baru dan memusatkan tugasnya "pada hal-hal yang amat strategis saja".
Dalam konteks penciptaan demokrasi atau keadilan ekonomi pada umumnya dan kemitraan pada khususnya, pemerintah dituntut untuk berperan sebagai pendidik, pembimbing, memfasilitasi kemitraan itu, menjadi pelopor, memberikan insentif dan disinsentif. Intinya pemerintah harus memotivasi dan tidak memaksa. Kecuali itu pemerintah harus mengurangi barriers to entry serta merangsang tumbuhnya pengusaha kecil (misalnya lewat pengembangan modal ventura dan dana penjamin, juga mengembangkan inkubasi bisnis) di satu pihak dan menjadi bemper penyelamat (misalnya menampung kelebihan produksi) bagi pengusaha kecil di pihak lain. Dengan kata lain, pemerintah memegang fungsi sebagai penjaga kepentingan umum dan persaingan yang sehat, pendorong kemitraan, pengatur distribusi manfaat dan kesempatan ekonomi serta menjalankan bisnis rintisan (yang kurang diminati swasta). Dalam konteks ini disamping secara keseluruhan efisiensi pelayanan birokrasi perlu ditingkatkan, Daerah juga perlu memperoleh wewenang yang lebih besar dalam pemberian ijin investasi. Lebih dari itu, yang secara teknis juga sangat penting bagi demokrasi ekonomi adalah bahwa analisis biaya dari setiap produk harus transparan dan perlu ditingkatkannya etika bisnis.
Bagaimana pembaharuan dapat dilakukan? Pembaharuan sebaiknya dimulai dari top administrators, yakni dari perumusan kebijakan, selanjutnya para tenaga profesional yang berdedikasi tinggi harus dapat menerjemahkan keinginan dan keputusan politik menjadi program-program yang konsisten dan efektif. Kecuali itu proses penyusunan kebijakan harus dilakukan dalam sistem musyawarah-mufakat yang dinamis dan jika perlu dikembangkan pula mekanisme debat publik, agar benar-benar terwujud suatu sistem manajemen yang partisipatif --sehingga sense of belonging masyarakat terhadap kebijakan dan programnya meningkat, sementara pemerintah juga terkondisikan untuk memilih sense of responsibility dan accountability yang tinggi.
6. Reorientasi birokrasi: membangkitkan enterpreneurialisme
Globalisasi sebagai tantangan dan peluang ekonomi dan keharusan perubahan bagi birokrasi pemerintah dibahas-ulang lagi dalam seminar yang diselenggarakan setahun kemudian, Juli 1996, oleh Pusdiklat Depdikbud. Kata kunci yang mengemuka dalam seminar ini adalah: reorientasi birokrasi. Berikut ini rangkuman dari enam makalah, yang masing-masing ditulis oleh empat orang dosen, seorang pengusaha dan seorang tokoh LSM.
"Globalisasi" perlu dibedakan dari internasionalisasi dan multinasionalisasi. Jika yang ke-dua merujuk pada ekspor-impor dan emigrasi-imigrasi, yang ke-tiga pada perluasan perusahaan ke luar negeri, globalisasi merujuk pada suatu "proses yang memungkinkan kejadian, keputusan dan kegiatan di satu bagian dunia mempunyai akibat penting bagi individu dan komunitas di bagian dunia lain yang (geografis) berjauhan." Globalisasi itu berlangsung tidak saja dalam hal cara kerja kapitalistik (keuangan atau modal dan pasar), melainkan juga teknologi, gaya hidup dan kesadaran, serta pemerintahan. Di tengah proses semacam itu, para aktor ekonomi didorong untuk berkompetisi, sedangkan negara terdorong untuk menjadikan wilayahnya sebagai lahan yang menarik bagi aktivitas bisnis. Negara harus mengurangi perannya untuk diberikan kepada swasta, menyediakan infrastruktur, membeirkan insentif pajak, menjamin adanya pasar dan mengamankan aspek perburuhan.
Namun, realitas globalisasi 1990-an adalah liberalisasi pasar finansial, yang dalam praktiknya bersifat spekulatif --menimbulkan ketidakpastian dan tidak produktif. Selain ketidakpastian, korporasi besar juga menggilas eksistensi perusahaan-perusahaan kecil, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Dengan kata lain: jurang perbedaan antar kelas semakin menganga. Karenanya dapat dikatakan bahwa jika dahulu (sebelum 1945) berlangsung kolonialisme dan imperialisme wilayah, saat ini berlangsung imperialisme ekonomi (contoh yang jelas: tergesernya buah-buahan lokal oleh impor) dan budaya (contoh yang jelas: dominasi informasi negara kaya lewat parabola dan internet). Mengingat hal ini, maka mestinya pemerintah tidak saja melulu menyediakan fasilitas bagi proses produksi kapitalis melainkan juga menerapkan kebijakan sosial guna menyediakan "jaring pengaman" bagi para aktor ekonomi kecil.
Tidak memperhitungkan dampak negatif seperti ditunjukkan Mas’oed di atas, para penulis yang lain --disadari atau tidak-- menerima globalisasi sebagai sesuatu yang tak terelakkan, yang "mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap" kita akan terlibat di dalamnya (lihat pernyataan Presiden di atas). Tjokrowinoto menyebutkan, bahwa teori ekonomi Keynesian yang mengandaikan adanya negara yang berdaulat penuh (dan karenanya ekonomi tertutup) dan menganjurkan pertumbuhan ekonomi berbasis permintaan telah tidak realistis lagi. Distorsi ekonomi pasar lewat intervensi pemerintah dalam bentuk lisensi, proteksi dan fasilitasi, yang semuanya --ditunjang oleh sentralisme-- berakibat pada kolusi dan korupsi dan akhirnya inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi harus dihapuskan. Birokrasi harus mengubah perilakunya menjadi lebih "tunduk" pada arahan pasar atau masyarakat daripada pada arahan aturan, dan dalam konteks ini birokrasi harus dapat menyesuaikan diri dengan variasi kontekstual serta kekhususan lokal (alias: desentralisasi atua otonomisasi). Birokrasi harus berkarakteristik enterpreneurial:
- sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru,
- tak terpaku pada kegiatan rutin, inovatif dan kreatif,
- futuristik dan sistemik,
- mampu memperhitungkan lalu meminimumkan risiko.,
- jeli terhadap sumber baru,
- mampu mengkombinasikan sumberdaya agar lebih produktif,
- mampu mengalihkan sumberdaya dari kegiatan yang kurang produktif ke yang lebih produktif.
Sementara itu Taufik melihat bahwa dalam era globalisasi ini terjadi pemaksaan nilai-nilai Barat (hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokrasi dan persaingan) ke Asia, padahal demokrasi a la Barat terbukti tidak mampu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Beranggapan bahwa demokrasi "musyawarah dan mufakat" dianggap lebih mampu menjaga stabilitas, dia tetap menyatakan bahwa globalisasi harus kita masuki dan daya saing Indonesia yang dinilai oleh lembaga internasional sangat rendah (tahun 1996 pada urutan ke-41 dari 48 negara yang dikaji) harus diperbaiki. Disamping ketertinggalan dalam limabelas hal di bidang kualitas manusia dan kemampuan manajemen, kekurangan Indonesia juga terletak pada infrastruktur yang kurang baik dan: birokrasi pemerintah yang buruk, administrasi pemerintah yang sentralistis, terjadinya kolusi, korupsi dan prosedur yang tak benar, serta adanya dominasi pasar oleh sedikit perusahaan atau adanya monopoli dan oligopoli karena belum tersedia undang-undang yang mengatur persaingan sehat. Lebih buruk lagi, ekonomi Indonesia cepat panas, dimana dengan pertumbuhan sekitar 7,5 persen menjadikan inflasi 10 persen, dan transaksi berjalan mengalami defisit yang mencapai 4 persen dari GNP. Bahkan pada 1996 kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya telah dapat dinilai sebagai "terpuruk dan amat memilukan", padahal dua tahun sebelumnya Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai "keajaiban Asia Timur" karena "suksesnya" dalam menciptakan pertumbuhan dan bertahan terhadap gejolak eksternal serta menurunkan jumlah penduduk miskin, dan majalah The Economist menyebut Indonesia pada 2020 berpeluang menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-lima di dunia (di bawah RRC, USA, Jepang dan India).
Karenanya Taufik menghendaki dilakukannya reformasi birokrasi, sehingga para pegawainya memiliki kualitas sebagai berikut:
- bersih dan berwibawa,
- profesional: cepat dan tepat dalam menanggapi masalah,
- berjiwa kewirausahaan, antisipatoris dan proaktif (termasuk kemampuan melobi bagi para pegawai perwakilan RI di luar negeri),
- tidak arogan, mempersulit prosedur, korup dan kolutif,
- dapat bekerjasama (teamwork) secara efektif dan efisien,
- memihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Untuk itu kondisi yang perlu diciptakan adalah:
- pemimpin bermoral dan dapat dijadikan panutan,
- hukum ditegakkan,
- kode etik diterapkan,
- gaji dan kompensasi setara dengan swasta,
- proses pembuatan keputusan terdesentralisasikan ke tingkat terendah,
- pendidikan dan pelatihan dilakukan terus-menerus.
Taufik tampak memberikan penekanan yang begitu besar pada persoalan pegawai. Padahal sebenarnya kondisi kepegawainegerian di Indonesia tidaklah sejelek yang dibayangkan, minimal telah mengalami perbaikan yang kontinyu. Dalam hal tingkat pendidikan, misalnya, di antara pertambahan seluruh pegawai dari 1982 hingga 1992 sebesar 12 persen (menjadi lebih dari 4 juta), pertambahan pegawai yang lulusan perguruan tinggi meningkat sebesar 48 persen, sebaliknya yang lulusan SLTP/A dan SD menurun masing-masing sebesar 7 dan 9 persen. Mengingat kemajuan ini (sekalipun kebanyakan terjadi pada kelompok guru), dan bahwa kualitas pendidikan masih selalu disinggung sebagai salah satu variabel yang lemah dari birokrasi kita, tampaknya "pendidikan" dalam artian non- dan informal-lah, yang praktis dan terkait jelas dengan posisi setiap pegawai, yang lebih perlu ditingkatkan. Bukan saja in house training yang perlu diperkenalkan secara meluas, melainkan evaluasi dan otokritik juga sangat penting, yang darinya terdeteksi dalam bidang apa seorang pegawai tidak mampu dan perlu "dididik" lebih lanjut. Keberanian untuk mengoreksi diri sendiri inilah yang terasa absen dalam praktik birokrasi sehari-hari, dimana setiap kesalahan cenderung ditutupi dan disebut sebagai kesalahan bersama. Lebih dari itu, tanpa adanya evaluasi maka kebijakan yang dirumuskan dalam bidang pendidikan dan latihan (baik kurikulum dan metode pendidikannya) sering terlepas dari konteks dan kebutuhan riil peserta pendidikan.
Variabel yang lebih krusial tampaknya adalah arogansi birokrasi (lihat daftar di atas), yang disoroti secara khusus oleh Sasono. Dia berpendapata bahwa arogansi merupakan dampak dari bureaucratic polity (lihat depan) yang telah "sukses" melancarkan program-program keluarga berencana, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan stabilitas. Arogansi itu tertampakkan sebagai penyelewengan, baik ke dalam birokrasi sendiri: pilih-kasih terhadap bawahan, tidak legal rasional, pengambilan keputusan yang berbelit-belit, prosedur pelayanan yang panjang dan koordinasi antar-instansi yang jelek; maupun ke luar: kolusi dengan dan pungutan liar kepada pengusaha. Dengan kalimat yang berbeda dapat dinyatakan bahwa arogansi itu merupakan penyakit birokrasi: mengutamakan kepentingan sendiri, pro status quo dan anti perubahan dan cenderung sentralisits. Beberapa di antara penyakit ini dapat disebut "biasa", sudah jamaknya, tetapi penyeleweangan berikut ini sudah melebihi batas toleransi masyarakat: kolusi di Mahkamah Agung, kredit macet, denda damai di jalan, biaya siluman dan kebocoran anggaran hingga 30 persen. Arogansi juga terwakili pada data yang diuangkap oleh sebuah penelitian ini: dalam hal pelayanan publik, pemerintah Daerah ternyata hanya mampu melaksanakan sekitar 44 persen fungsinya, sedangkan dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat mereka paling sedikit dapat mencapai 75 persen. Karena itu, baginya, tidak ada cara lain yang dapat ditempuh kecuali melakukan "perbaikan birokrasi secara menyeluruh", baik pada aspek institusional maupun kultural. Ide "perbaikan yang menyeluruh" ini kelihatannya dua tahun kemudian diterjemahkan sebagai "reformasi" --yang secara politis terwujud sebagai penggantian penguasa pada Mei 1998.
7. Reformasi administrasi ke-dua: desakralisasi dan dekonstruksi negara (atau: rasionalisasi dan demokratisasi lagi)
Tiga bulan setelah Gerakan Reformasi Mei 1998 diselenggarakan sebuah seminar bertema reformasi birokrasi publik oleh Pusdiklat Pegawai Depdikbud, dengan empat orang pembicara yang kesemuanya dosen --satu ahli administrasi negara, satu sosiolog dan dua politolog. Wignyosoebroto menyebut kebutuhan akan dekonstruksi dan rekonstruksi birokrasi agar tetap berfungsi dalam zaman yang telah berubah. Mula-mula adalah dengan mendeskralisasikan birokrasi (salah satu tema sentral Gerakan Reformasi) dan menciptakan birokrasi yang profan, rasional dan profesional. Legal-rasionalisasi birokrasi ini sebenarnya telah dimulai sejak jaman kolonial abad ke-19, tapi gagal, dan era Soeharto malah melestarikan sakralisasi birokrasi itu (lihat bab ke-dua dan ke-tiga). Namun, Wignyosoebroto kemudian mempersoalkan, apakah birokrasi legal-rasional a la Weber itu (seandainya dia dapat terwujud-sempurna di Indonesia) masih akan fungsional dalam peralihan milenium ini? Dijawabnya, bahwa birokrasi mendatang haruslah birokrasi yang tidak birokratis, yang melakukan kolaborasi dengan mereka yang bebas (privat), yang bekerja lebih secara konsensual daripada secara hierarkhies, yang terbuka bagi pengamatan publik.
Dalam bentuknya yang ideal, menurut Usman, birokrasi memiliki karakteristik sebagai berikut:
- bekerja dengan rencana dan ber-aturan atas dasar legal contract (karena itu ada hubungan atasan-bawahan),
- impersonal, obyektif, tidak memihak,
- rasional, lepas dari kepentingan sesaat,
- para pegawainya adalah orang yang ahli yang direkrut dan dipromosikan lewat seleksi berdasar prestasi (achieved status) dan bukannya keturunan (ascribed status) dan
- mereka bekerja secara terspesialisasi.
Selama ini prinsip impersonal itu tidak terwujud, karena rekruitmen birokrati ditentukan oleh jaringan informal dan sentimen pribadi yang terbentuk lewat jargon agama, suku dan daerah --yang membentuk suatu paguyuban semu (pseudo-gemeinschaft). Samego juga mengatakan, bahwa keputusan pejabat enjati tidak obyektif dan tidak terukur, bahkan mereka sering melanggar keputusannya sendiri. Ini semua harus dihentikan, karena di satu pihak berlangsung arus global governance, dimana persoalan dalam negeri seringkali harus dikelola dalam secara internasional, dan di pihak lain masyarakat telah mengalami mobilisasi intelektualitas yang cukup berarti. Mereka menjadi jauh lebih kritis, ingin dihargai, membutuhkan aktualisasi diri, dan karenanya menghendaki suatu fair play. Jadi tampaknya diandaikan oleh Usman bahwa birokrasi yang ideal itu mampu menyediakan arena bermain yang adil bagi semua aktor. Benarkah asumsi ini?
Mengharapkan pejabat untuk selalu bersikap adil dan impersonal tampaknya --sekalipun tidak mungkin-- adalah hal yang sangat sulit. Karena mereka adalah person yang memiliki kepentingan, dan dalam konteks kepentingan-pribadi mereka itulah kata "rasional" dimengerti. Dengan mengutip teori rational choice, Mas’oed berusaha menjelaskan mengapa dalam tubuh birokasi terjadi korupsi. Karena dunia ini "penuh dengan kelangkaan", misalnya bahwa kita ini memiliki waktu, energi, kemampuan dan pendapatan yang terbatas, maka kita harus selalu memilih dan pilihan itupun tidaklah leluasa melainkan dibatasi oleh aturan main, nilai, norma, undang-undang, informasi dan harga. Kepentingan seorang politisi dan pejabat bisa bermacam-macam: kekuasaan, gaji, kepuasan dalam melayani atau menyaksikan akibat dari undang-undang yang dibuatnya. Untuk meraih kepentingan ini mereka pertama-tama harus terpilih sebagai anggota parleman atau diangkat sebagai pejabat --politisi harus memperoleh dukungan dari pemilih, penyumbang dana kampanye dan partai politik; sedangkan pejabat harus disenangi oleh atasannya. Dalam situasi semacam ini jika lembaga masyarakat tidak terorganisasi secara kuat dan karenanya tidak mampu mengontrol perilaku politisi dan pejabat, maka korupsi akan merajalela. Para pelaku bisnis cenderung untuk mengeruk keuntungan lewat lembaga negara (dengan meminta proteksi atau monopoli) yang diperolehnya lewat suap dan nepotisme (korupsi) dan ini merugikan kesejahteraan masyarakat, bukannya lewat pasar (membuat usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan baru) yang menguntungkan orang banyak.
Oleh karena itu solusinya adalah: mengurangi intervensi negara terhadap pasar dan bersamaan dengan itu menghilangkan peluang korupsi. State corporatism (kontrol negara atas semua kelompok kepentingan) harus dihapus, persaingan harus dibiarkan terbuka: demokrasi, check and balances antar lembaga kekuasaan, serta pengawasan sosial. Menurut Samgeo, ini tampaknya merupakan pra-kondisi yang sangat penting, karena selama ini, sejak dulu sampai sekarang, dalam setiap pendidikan politik dan pendikan-pelatihan pegawai negeri selalu diajarkan nilai-nilai birokrasi modern dan juga prinsip-prinsip pelayanan dan kewirausahaan, namun dalam praktik tidak terlihat wujudnya.
8. Rangkuman
Penjelasan di atas kiranya telah memberikan informasi tentang model perubahan administrasi yang dipilih pemerintah-pemerintah di Nusantara untuk merespon perkembangan lingkungan sosial, politik dan ekonominya. Sebagaimana divisualisasikan pada gambar, perubahan administrasi dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19, ketika pemerintahan Raffles berusaha memodernisasikan administrasinya sesuai dengan semangat zaman: munculnya negara bangsa dan terjadinya revoluasi industri di Eropa dengan segenap nilainya --rasional, analitik, serba tertulis dan efisien. Ketika kemerdekaan melepaskan keterkekangan yang lama, mekarlah demokrasi politik yang ironisnya melahirkan nepotisme. Ini direspons dengan rasionalisasi administrasi. Ketika kemudian pemerintah berhasil menguasai sistem politik, mereka mengundang masuknya modal asing dan melancarkan program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu digunakanlah model administrasi pembangunan. Namun ketika dana pemerintah berkurang, mereka mengurangi perannya melalui proses deregulasi dan debirokratisasi. Ini berlanjut terus hingga ketika dirasakan perlunya mempersiapkan diri menghadapi globalisasi perdagangan dan melesatnya teknologi informasi dirasakan perlunya mempertegas modernisasi administrasi lagi. Terakhir, ketika demokrasi "terbatas" selama pemerintahan pembangunan mulai dirasakan terlalu pengap, diusulkanlah perubahan administrasi dalam bentuknya reformasi administrasi.